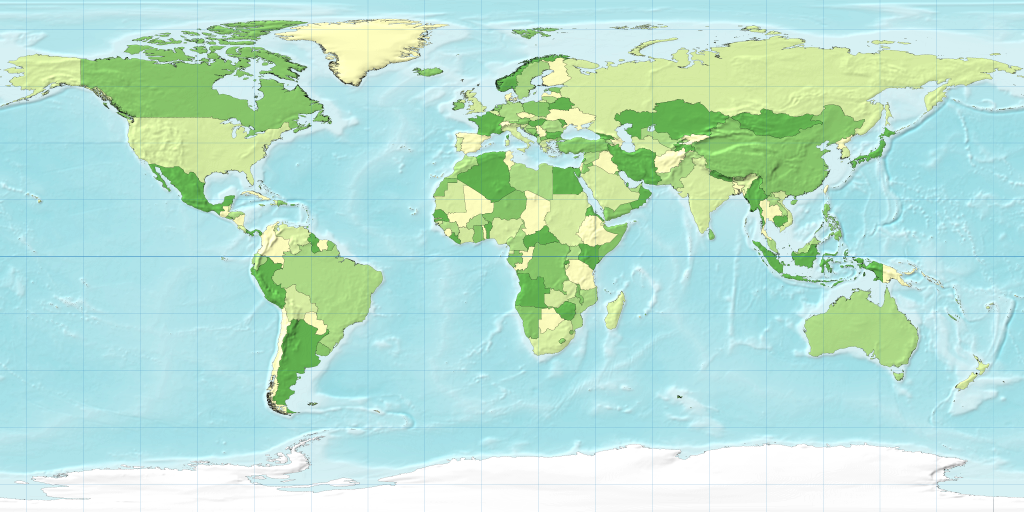Bursa saham AS kembali kembali bergolak. Imbasnya
pasar modal di kawasan Eropa dan Asia Pasifik juga
juga berguncang. Indeks Straits Times Singapura, Hang
Seng Hong Kong dan Nikkei Tokyo misalnya, mengalami
koreksi yang cukup signifikan. Indeks harga saham
gabungan (IHSG) di bursa Efek Jakarta juga melorot di
bawah level 2.200 meski beberapa hari kemudian
mengalami perbaikan. Sejumlah analisis memperkirakan
sekitar US$ 2,66 triliun dana investasi keluar dari
pasar saham Asia (Tempointeraktif, 7 Agustus).
Kegoncangan ini sebagaimana yang dirilis oleh the
Economist bermula dari krisis kredit yang menimpa
sejumlah perusahaan sub prime mortgage di AS,
perusahaan pemberi kredit perumahan yang khususnya
ditujukan bagi mereka yang memiliki pendapatan yang
rendah. Perusahaan ini selanjutnya menerbitkan surat
berharga dengan jaminan perumahan tersebut yang dijual
di pasar modal. Para spekulan kemudian membeli
surat-surat berharga tersebut dengan harapan di masa
yang akan datang harga rumah yang menjadi jaminan
surat berharga tersebut. Karena peminatnya semakin
banyak baik individu maupun perusahaan maka nilainya
terus menggelembung melampaui nilai riil properti yang
dijadikan jaminan.
Lama kelamaan harga rumah tidak lagi didasarkan pada
tingginya permintaan terhadap rumah namun pada
tingginya permintaan terhadap surat utang tersebut.
Tragisnya gelembung penjualan surat mortgage yang
mulai marak di era 90-an ini kembali meledak.
Pemicunya pernyataan sejumlah pemilik perusahaan
mortgage yang menyatakan bahwa sejumlah peminjam yang
berbasis jaminan perumahan tak lagi mampu membayar
utang mereka (default).
Dampaknya para investor baik yang memegang surat
mortgage tersebut panik dan berlomba menjual
surat-surat berharga tersebut (panic selling). Karena
semakin banyak yang menjual surat berharga itu maka
nilainya pun terus anjlok. Akibatnya banyak investor
baik yang berbentuk perorangan maupun lembaga yang
mengalami kerugian bahkan tidak sedikit yang bangkrut.
Sebelumnya pada bulan Maret 2007 sekitar puluhan
perusahaan sub prime AS mengalamai kebangkrutan
termasuk yang paling besar New Century Financial.
Utang publik yang ditinggalkan sekitar 8,5 triliun
dollar atau tujuh kali jumlah uang beredar (M1) yang
berjumlah 1,3 triliun dollar AS (Khilafah.com, 22/8).
Berikutnya, bank-bank yang telah mengucurkan dananya
untuk pembiayaan sektor perumahan tersebut mengalami
kesulitan modal. Bank Sentral AS, Federal Reserve
terpaksa melakukan intervensi dengan menurunkan
tingkat suku bunga pinjaman perbankan (discount rate)
dari 6,25 menjadi 5,75 persen. Diperkirakan lebih dari
800 miliar dollar AS telah dikucurkan oleh bank-bank
sentral di seluruh dunia untuk meredakan krisis ini.
(Khilafah.com, 22/8). Bank Sentral Eropa saja pada
tanggal 9 Augstus saja mengucurkan 131 miliar dollar
AS ke pasar modal. (Economist, 9/8)
Di dalam negeri, gejolak sektor keuangan ini membuat
sejumlah investor khususnya asing melakukan aksi
profit taking dengan mengalihkan investasi mereka ke
dalam dolar. Akibatnya, nilai tukar rupiah juga
terpuruk mendekati Rp. 9.500 per dollar. Bank
Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter pun
berupaya meredam gejolak ini dengan terus menggelontor
cadangan devisanya agar rupiah tidak terdepresiasi
terlalu jauh. (Kompas, 18/8/07).
Namun demikian pihak pemerintah menanggapi masalah ini
dengan dingin. Menurut Sri Mulyani keadaan ini tidak
akan menjurus pada krisis yang lebih parah.
Fundamental Ekonomi juga dianggap cukup kuat. Bahkan
Presiden SBY menyerahkan sepenuhnya penyelesaian
masalah ini kepada negara-negara besar (KoranTempo,
18/8).
Penyakit Bawaan
Goncangan moneter di dalam sistem keuangan
kapitalistik memang fenomena umum yang efeknya sangat
mengganggu bahkan kadang mematikan. Perjalanan sistem
ini telah diwarnai sejumlah krisis, sebut saja
misalnya depresi ekonomi tahun 1929, 1980, dan 1987.
Buku laris Profesor Charles P. Kindleberger: Manias,
Panics, and Crashes: A History of Financial
Crises(1996) telah mengurai kejadian-kejadian tersebut
secara detail. Pengalaman krisis yang belum pudar dari
ingatan bahkan efeknya masih teras sampai sekarang
adalah krisis moneter yang melanda kawasan Asia tahun
1997.
Salah satu faktor penyangga sistem ini adalah adanya
pasar uang dan pasar saham yang menjadi tempat
transksi modal dan mata uang yang spekulatif. Termasuk
dalam hal ini adalah penjualan mortgage secuties. Pada
faktanya transaksi yang terjadi di sektor nonriil ini
jauh melampuai jumlah transaksi di sektor riil.
Menurut The Economist (16/6/01) pada tahun 1971, tidak
kurang dari 90 persen transaksi finansial terkait
dengan ekonomi non riil dalam berbagai macam investasi
jangka panjang dan hanya 10 persen yang digunakan
untuk spekulasi. Namun keadaan kemudian berbalik.
Tahun 1996 saja, sekitar 95 persen dari 1,2 dollar AS
transaksi finansial global perhari berupa spekulasi,
dan 80 persen diantaranya merupakan spekulasi
mondar-mandir dengan kecepatan 1-7 hari (Deliarnov,
2006).
Krisis Sub-Prime morgage ini mirip dengan krisis yang
melanda Thailand tahun 1997 yang kemudian memberi efek
domino (contagion effect) ke sejumlah negara di
kawasan Asia. Sebelumnya, negara ini dipuja karena
masuk dalam kategori negara yang mengalami pertumbuhan
yang fantastis. Namun pujian itu berakhir dengan
meledaknya balon ekonomi negara tersebut (bubble
economic). Pemicunya adalah pembangunan real estate
yang terus berlangsung tidak diimbangi oleh
peningkatan daya beli masyarakat yang terus merosot.
Sejumlah Perusahaan real estate terkemuka kemudian
tidak mampu membayar utangnya kepada sejumlah bank.
Para investor saham yang lebih cerdik mulai menarik
dana mereka. Keprihatinan kemudian berubah menjadi
kepanikan. Saham-saham kemudian anjlok. Intervensi
pemerintah Thailand sebesar 9 miliar USD tidak banyak
menolong. Bahkan para spekulan mengambil keuntungan
dari intervensi tersebut. Satu juta orang thailand
dalam waktu tiga bulan kehilangan pekerjaan. Demikian
pula pinjaman pemerintah kepada IMF sebesar 17,2
miliar dollar AS untuk membayar utang luar negeri
perusahaan keuangan, tidak banyak membantu. Meski
demikian para spekulator telah menangguk keuntungan
dari kerapuhan sistem ekonomi negara tersebut (Walden
Bello, â€The End of the Asian Miracle†1998 dalam
Korten).
Krisis yang menimpa Thailand tersebut kemudian melanda
negara-negara Asia lainnya. Indonesia kehilangan lebih
dari 15 persen tenaga kerjanya pada bulan Agustus
1998. Di Korea Selatan angka kemiskinannya naik tiga
kali lipat. Lebih dari seperempat penduduknya menjadi
miskin. GDP Indonesia jatuh sebesar 13,1 persen, Korea
6,7 persen dan Thailand 10,8 persen. Ini membuktikan
bahwa struktur keuangan dan moneter negara-negara
tersebut amat rentan sebagaimana halnya dengan
negara-negara lain. Meski menurut Stiglitz (2002)
liberalisasi (sektor keuangan) tetap merupakan faktor
yang paling penting yang memicu krisis tersebut.
Liberalisasi Sektor Keuangan
Dalam menjalankan transaksinya para investor keuangan
senantiasa bertindak spekulatif. Ia akan membeli saham
tertentu jika ia memprediksi bahwa bahwa di masa yang
akan datang akan lebih tinggi dari harga belinya.
Sebaliknya jika ia memprediksi bahwa harganya akan
turun maka ia pun melepas sahamnya yang mengakibatkan
indeks harga saham perusahaan tersebut menurun. Jika
kepanikan ini berlangsung secara massif dimana
tindakan tersebut diikuti investor lainnya dengan
menjual saham-saham mereka maka dipastikan saham
perusahaan tersebut akan anjlok bahkan gulung tikar.
Dampak berikutnya adalah menurunya produksi dan
membengkaknya angka pengangguran. Inilah yang menimpa
Enron, salah satu perusahan terbesar di AS yang
bermarkas di Texas. Hal yang sama juga menimpa
World.Com yang harga sahamnya anjlok hingga 94 persen.
Enron yang mempekerjakan 85. 000 orang di 65 negara
tersebut akhirnya bangkrut dan terpaksa merumahkan
seluruh karyawannya (Butt, 2002).
Para spekulan tak lagi peduli pada dampak yang mereka
timbulkan. Watak ini memang tidak bisa dipisahkan dari
para pelaku ekonomi dalam sistem Kapitalisme
sebagaimana yang dinyatakan oleh Friedeman dalam
Capitalism and Freedom (1962): â€ada satu dan hanya
satu, tanggungjawab sosial perusahaan atau bisnis,
yaitu menggunakan seluruh sumber daya yang mereka
miliki untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknyaâ€
Meski telah mengalami getirnya krisis keuangan,
Indonesia dan negara-negara Kapitalis lainnya tetap
tak bergeming dengan sistem moneter yang liberal ini.
Rezim devisa bebas misalnya tetap dipertahankan. Nilai
tukar dapat mengambang bebas sehingga membuat nilai
tukar dapat berfluktuasi tanpa batas. Uang-uang panas
(hot money) yang berjangka pendek bisa keluar masuk
mencari imbal hasil yang tinggi dari satu negara ke
negara lainnya tanpa mengalami hambatan berarti.
Sebaliknya sektor riil terus mengalami ketidakstabilan
harga akibat fluktuasi nilai tukar ini. Akibatnya
derajat ketidakpastian usaha semakin besar.
Padahal menurut Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi tahun
2001, di banyak negara berkembang liberalisasi modal
dan pasar keuangan, justru menciptakan ketidakstabilan
dan tidak menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, Bahkan.
India dan China yang pertumbuhan ekonominya tinggi
terhindar dari krisis Asia tahun 1997 tanpa melakukan
liberalisasi. (Kompas, 13/8/07).
Salah satu dampak dari buruknya leberalisasi sektor
keuangan juga dinyatakan oleh Robert Mundell (1983)
profesor ekonomi dari Universitas Colombia yang
menyimpulkan bahwa dalam sistem pertukaran mata uang
mengambang (floating rate) maka cadangan devisa lebih
banyak dibutuhkan dibandingkan dengan sistem kurs
tetap (fixed rate). Cadangan mata uang yang digelentor
tersebut ternyata juga sering kali tidak efektif dan
malah jatuh ke kantong-kantong spekulan. Sebagai
contoh, ketika IMF dan pemerintah Brazil melakukan
intervensi pasar sekitar 50 miliar dollar untuk
menjaga nilai tukar yang mengalami overvaluasi pada
akhir 1998, uang tersebut seakan hilang ditelan angin.
Uang tersebut justru mengalir ke para spekulan. Bahkan
Stiglizt (2003) menuduh bahwa IMF-lah yang justru
menjaga agar para spekulan tersebut tetap dapat
menjalankan profesinya.
Negara-negara yang mata uangnya dijadikan sebagai
cadangan devisa oleh negara-negara lain juga
mendapatkan keuntungan sehingga terus terdorong untuk
memproduksi mata uangnya sebagaimana yang dilakukan
oleh AS. Saat ini defisit anggaran belanja Amerika
mendekati US$1 triliun pada akhir tahun ini sangat
mengkhawatirkan pelaku pasar modal khususnya investor
non-Amerika. Bukan itu saja menurut Direktur General
Accounting Office (GAO) pada 2005, kekayaan federal
hanya sekitar US$1 triliun sedangkan utangnya telah
mencapai US$7 triliun. Artinya, defisit kekayaannya
telah mencapai US$ 6 triliun. Meski demikian,
gelembung dollar terus saja dipompa oleh AS yang entah
kapan gelembung itu akan meledak. Wajar jika AS dan
korporat-korporat yang selama ini meraup keuntungan
dari liberasasi ekonomi terus mempertahankan
eksistensi sistem ini.
Kembali Ke Syariah
Memang, sejak runtuhnya standar emas dimana mata uang
yang beredar dipatok oleh emas yang kemudian disusul
oleh runtuhnya sistem Bretton Woods tahun 1971, sistem
mengkaitkan supply dollar dengan emas, krisis moneter
dan keungan menjadi fenomena umum. Tiap-tiap negara
telah mencetak mata uangnya kertas tanpa ditopang oleh
sesuatu yang bernilai seperti emas dan perak kecuali
jaminan dari pemerintah semata atau oleh mata uang
kertas yang juga rapuh seperti dollar. Hal tersebut
sebagaimana yang dinyatakan oleh Paul Krugman (2005)
telah menyebabkan penderitaan yang sangat besar
khususnya bagi para pelaku ekonomi.
Wajar jika sejumlah ekonom menyerukan untuk kembali
kepada standar emas dan perak. Termasuk dalam hal ini
seruan untuk menghapus berbagai bentuk
transaksi-transaksi non riil di bursa-bursa saham yang
telah menjadi meja judi raksasa oleh para spekulan,
tidak sebatas mengenakan restriksi pajak untuk
membatasi ruang gerak mereka. Pada saat yang sama
pemerintah harus menata seluruh transaksi-transaksi
kapitalistik yang ada agar sejalan dengan tuntunan
syariah termasuk menghapus praktek-praktek ribawi yang
dijalankan bank-bank dan lembaga keuangan
konvensional.
Mempertahankan sistem perekonomian saat ini jelas
hanya akan berakibat pada malapetaka berkepanjangan.
Goncangan demi goncangan akan terus terjadi. Tapi,
sampai kapan umat manusia harus menderita? ila mata?
वास्सलम.